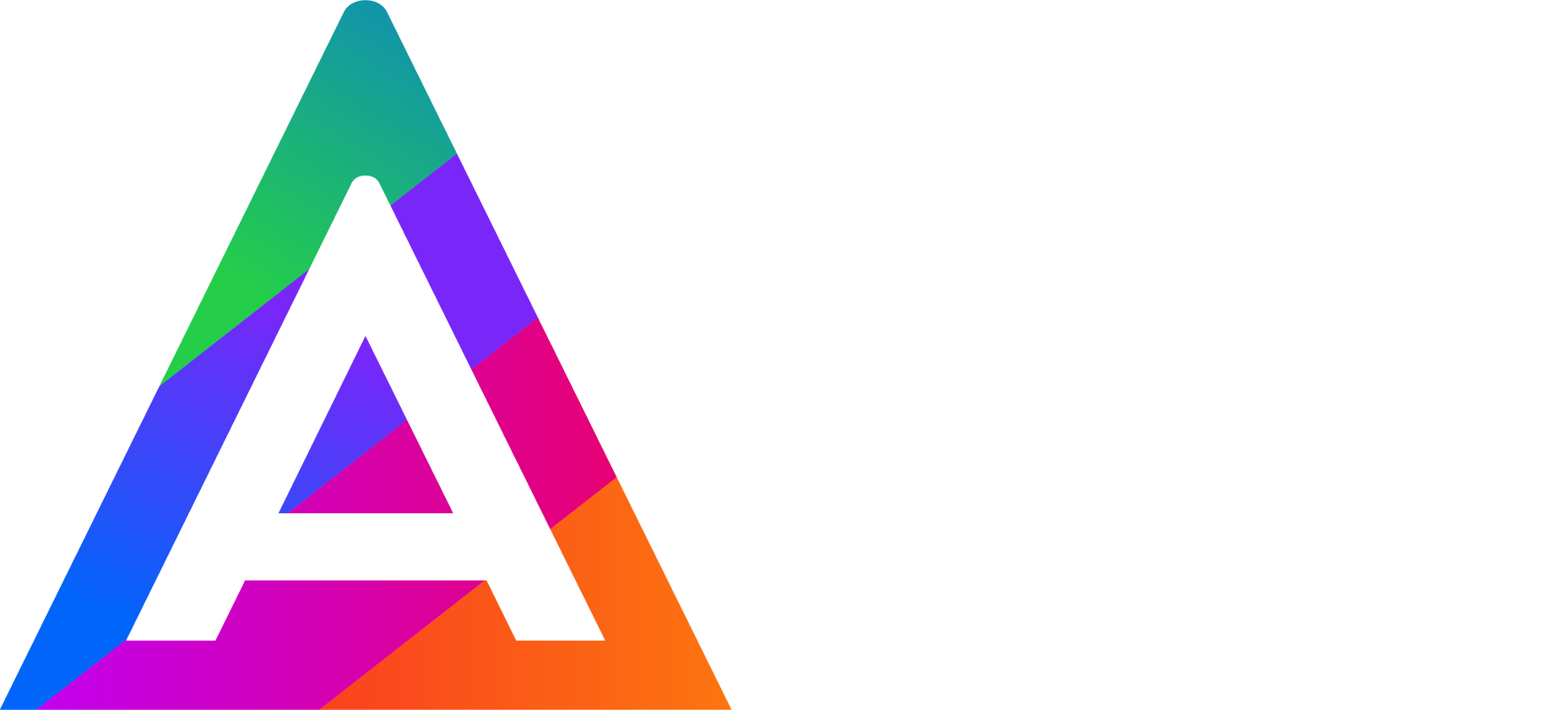Jakarta, AAD Today - Industri perfilman Indonesia mencatat prestasi gemilang pada 2024 dengan menguasai 65 persen pangsa pasar bioskop domestik dan meraih lebih dari 80 juta penonton. Pencapaian ini semakin diperkuat oleh kesuksesan film animasi "Jumbo" yang pada kuartal pertama 2025 berhasil menembus angka 10 juta penonton, menjadi film terlaris sepanjang masa dalam sejarah perfilman Indonesia.
Namun, di balik gemerlap angka-angka tersebut, para pengamat industri mempertanyakan apakah kemajuan ini mencerminkan fondasi ekosistem yang kokoh atau sekadar fenomena sementara. Dalam dua tahun terakhir, sekitar 100-150 judul film Indonesia telah dirilis di bioskop, namun keragaman genre masih menjadi persoalan utama. Data menunjukkan bahwa genre drama mendominasi dengan 49,5 persen, diikuti horor sebesar 30,5 persen. Sementara itu, genre lain seperti kriminal, politik, detektif, dan fiksi ilmiah hampir tidak tersentuh.
"Ini mencerminkan ketimpangan dalam eksplorasi narasi dan bentuk, padahal Indonesia memiliki 38 provinsi dengan kekayaan budaya dan sejarah lokal yang luar biasa," ungkap seorang pengamat film yang tidak ingin disebutkan namanya. Fenomena film "Jumbo" yang meraih lebih dari 10 juta penonton dalam kuartal pertama 2025 menandai pencapaian baru yang pertama kali terjadi sepanjang sejarah film di Indonesia.
Sebagai perbandingan, Tiongkok telah merancang strategi layar nasional yang efektif dengan membanjiri bioskop menggunakan film lokal dan menyuntikkan kebijakan proteksionisme. Berdasarkan data China Film Administration, pangsa pasar film lokal di Tiongkok mencapai 83,8 persen pada 2023. Negara tersebut juga membatasi jumlah film asing sekitar 34 film per tahun berdasarkan sistem kuota, membuktikan bahwa jika dikelola dengan benar, industri film dapat menjadi mesin ekonomi sekaligus alat diplomasi budaya yang strategis.
Lebih dari sekadar volume dan genre, kualitas konten merupakan fondasi esensial dalam mengukur kemajuan perfilman Indonesia. Peningkatan jumlah film tidak serta-merta mencerminkan kematangan narasi, kedalaman penyutradaraan, kualitas akting, ataupun perkembangan signifikan dalam aspek teknis seperti sinematografi, tata suara, penyuntingan, bahkan teknologi visual seperti CGI. Film yang mampu menyajikan cerita orisinal, dieksekusi dengan teknik mumpuni, dan diperankan dengan penghayatan mendalam memiliki potensi daya tahan yang lebih lama serta peluang untuk diapresiasi di tingkat internasional.
Meskipun beberapa karya film dari Indonesia sempat mencuri perhatian di panggung global dalam beberapa tahun terakhir, hal itu belum cukup menegaskan keberadaan sinema Indonesia dalam lanskap sinema dunia. Keberhasilan yang muncul masih terkesan sebagai pencapaian individu yang bersifat insidental, bukan hasil dari fondasi ekosistem yang kokoh. Tanpa strategi kebudayaan yang terarah dan keberpihakan struktural, industri ini terus-menerus merayakan keberuntungan, bukan keberlanjutan.
Kemajuan perfilman memerlukan kemajuan ekosistem yang seimbang meliputi pendidikan, regulasi, distribusi, lembaga kebudayaan, dan dukungan politik. Negara-negara dengan industri film mapan memiliki badan publik yang kuat, seperti Korean Film Council (Kofic) di Korea Selatan, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) di Prancis, atau British Film Institute di Inggris.
Indonesia sebenarnya memiliki Badan Perfilman Indonesia (BPI), lembaga yang dibentuk untuk fungsi serupa. Namun, hingga hari ini BPI belum menunjukkan fungsinya secara strategis. Tanpa dasar hukum yang kokoh dan dukungan anggaran yang memadai, BPI justru bergerak gamang. "Alih-alih menggarap isu-isu makro seperti kebijakan, distribusi, dan infrastruktur ekosistem, para pengurusnya sering terjebak pada urusan mikro yang salah sasaran," kritik seorang praktisi film. Tanpa dukungan hukum yang kuat dan anggaran yang memadai, BPI menjelma menjadi cerminan kebijakan tanpa arah dan enggan berpikir jauh ke depan.
Jakarta sebagai pusat utama produksi film nasional yang menyumbang porsi besar aktivitas perfilman di Indonesia, belum memiliki komisi film (film commission) yang memfasilitasi izin, lokasi, dan sinergi antarinstansi. Di negara lain, komisi film bukan sekadar fasilitator teknis, melainkan motor penggerak industri. Tokyo membentuk komisi film sejak 2001 dan Filipina melalui Quezon Film Commission sejak 2006. Ketiadaan infrastruktur ini membuat produksi film nasional berjalan dalam sistem yang tidak efisien, mahal, dan sering bergantung pada jalur informal.
Masalah paling mendesak justru ada pada tingkat pekerja film. Sebagian besar mereka berstatus pekerja informal, tanpa kontrak kerja, standar upah nasional, jaminan keselamatan, ataupun pelindungan dari perundungan dan kekerasan seksual di lingkungan syuting. Banyak profesi seperti colorist, stunt coordinator, pembuat efek visual, dan kru film lain yang belum memiliki asosiasi atau pelindungan struktural. Saat film Indonesia terus diputar di bioskop, pelakunya tetap hidup dalam ketidakpastian.
Pendidikan film pun masih terjebak dalam pendekatan teknis. Kurikulumnya lebih menekankan pada produksi dan penyutradaraan, tanpa cukup ruang bagi studi kuratorial, sejarah sinema, ekonomi film, atau kritik film. Padahal ekosistem film tidak bisa hidup dari produksi semata. Peran negara seharusnya hadir dalam konteks ini karena film bukan sekadar produk hiburan, melainkan instrumen pertukaran pengetahuan, medium refleksi sosial, dan bahkan alat soft power yang efektif. Hollywood sudah lama menjadi ujung tombak ideologis Amerika Serikat.
Festival Film Internasional Venesia yang berdiri sejak 1932 bahkan tidak berhenti saat Perang Dunia berkecamuk. Bahkan negara seperti Qatar dan Uni Emirat Arab menyuntikkan dana miliaran dolar Amerika Serikat untuk membangun festival serta institusi perfilman global. Saat ini Indonesia memiliki dua kementerian yang bersinggungan langsung dengan sektor film, yakni Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Ekonomi Kreatif. Idealnya, Kementerian Kebudayaan mengemban peran ideologis dan kebudayaan, memastikan film menjadi wahana nilai, ekspresi identitas, dan diplomasi budaya. Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif menjadi penggerak industri yang menghadirkan investasi, akses pasar, dan distribusi.
Namun, kenyataannya, pembagian peran ini belum tampak jelas. Dalam forum-forum antara orang film dan Kementerian Kebudayaan, diskusi justru masih berkutat pada jumlah penonton, jumlah layar, dan volume produksi. Padahal kementerian ini seharusnya membahas regenerasi pelaku seni, penguatan ekosistem film, dan memperkuat kekuatan imajinasi bangsa. Hingga kini belum terjadi sinergi di antara kedua kementerian tersebut. Keberhasilan dan rencana yang terus digaungkan masih berkutat pada angka produksi dan penonton, bukan pada infrastruktur jangka panjang.
Jika Indonesia ingin menjadikan film sebagai kekuatan kultural dan ekonomi, negara harus membangun kebijakan jangka panjang, bukan sekadar hadir saat festival di luar negeri atau membuat program insidental. Negara tidak membatasi kebebasan berekspresi, tapi wajib menciptakan ekosistem yang adil, inklusif, bebas dari konflik kepentingan, regeneratif, dan berkelanjutan.
Menjawab pertanyaan apakah film Indonesia telah maju, para pengamat sepakat bahwa jawabannya adalah belum. Film Indonesia sedang bergerak dengan energi luar biasa, namun yang dibutuhkan bukan hanya kebanggaan atas jumlah penonton dan jumlah judul film, melainkan juga kesadaran bahwa di balik layar ada sistem yang mesti diperbaiki. Seperti sebuah film yang baik, kemajuannya dibangun lewat naskah yang terstruktur, visi yang jelas, dan eksekusi yang konsisten untuk menciptakan fondasi ekosistem yang kokoh dan berkelanjutan.