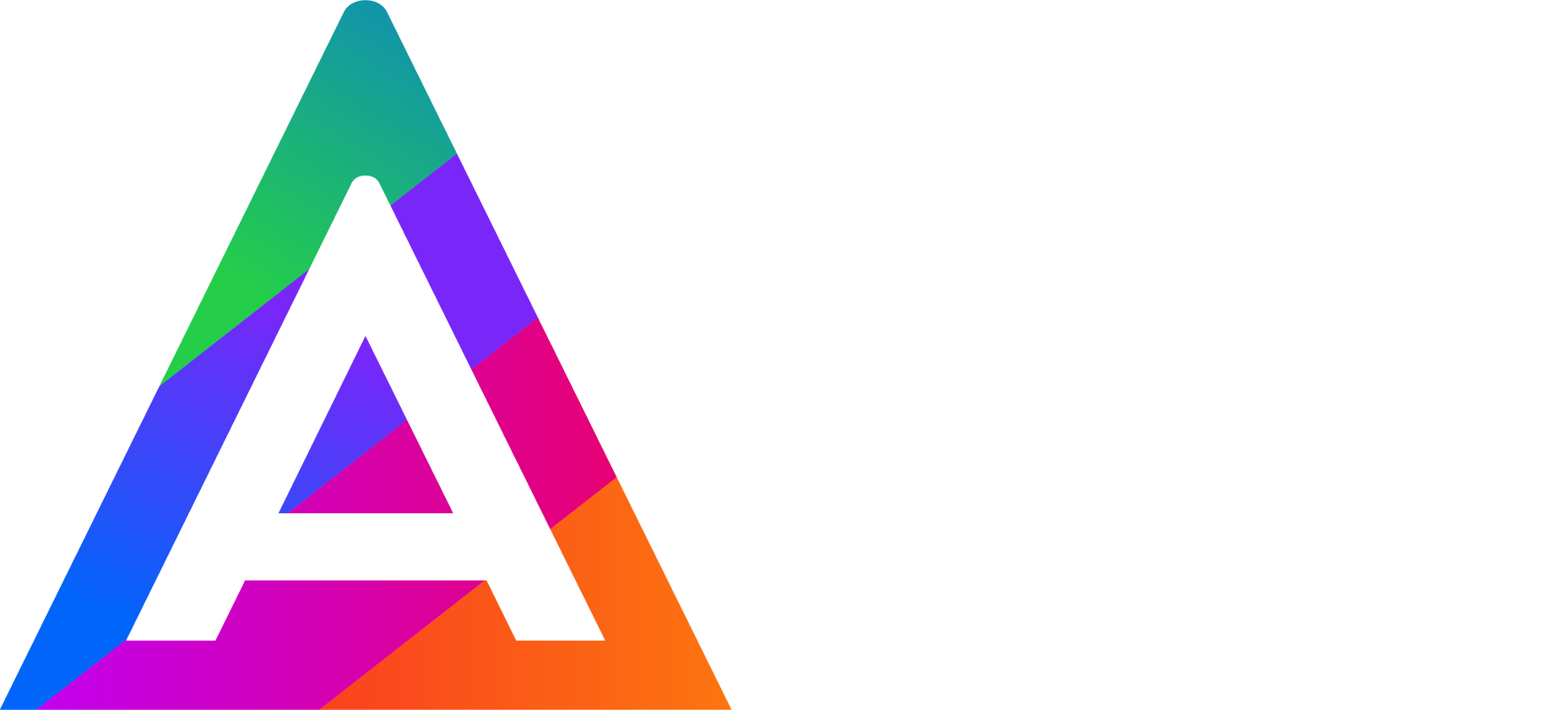Sultan Agung (bahasa Jawa: ꦱꦸꦭ꧀ꦠꦤ꧀ꦲꦒꦸꦁꦲꦢꦶꦥꦿꦧꦸꦲꦚꦏꦿꦏꦸꦱꦸꦩ, translit. Sultan Agung Adi Prabu Anyakrakusuma; lahir di Kotagede, 1593 ? meninggal di Karta, 1645) merupakan sultan Mataram ketiga yang memerintah dari tahun 1613 hingga 1645. Beliau dikenal sebagai seorang sultan sekaligus senapati ing ngalaga (panglima perang) yang terampil dalam membangun negerinya dan mengkonsolidasikan kesultanannya menjadi kekuatan teritorial dan militer yang besar.
Silsilah dan Keluarga
Nama asli Sultan Agung adalah Raden Mas Jatmika, yang juga dikenal sebagai Raden Mas Rangsang. Beliau merupakan putra dari Susuhunan Anyakrawati, raja kedua Kesultanan Mataram, dan Ratu Mas Adi Dyah Banawati, putri dari Pangeran Benawa, raja terakhir Kesultanan Pajang. Terdapat versi lain yang menyatakan bahwa Sultan Agung adalah putra Raden Mas Damar (Pangeran Purbaya), cucu Ki Ageng Giring, namun versi ini masih perlu dibuktikan kebenarannya.
Sultan Agung memiliki dua permaisuri utama sesuai tradisi Kesultanan Mataram, yakni Ratu Kulon dan Ratu Wetan. Ratu Kulon bernama asli Ratu Mas Tinumpak, putri dari sultan Kesultanan Cirebon, yang melahirkan Raden Mas Syahwawrat (Pangeran Alit). Sedangkan Ratu Wetan bernama asli Ratu Ayu Batang, putri dari Adipati Batang sekaligus cucu Ki Juru Martani, yang melahirkan Raden Mas Sayyidin, yang kemudian dikenal sebagai Amangkurat I.
Sepanjang hidupnya, Sultan Agung menikah dengan tiga istri permaisuri dan beberapa istri selir, dengan total 12 orang anak.
Gelar dan Kenaikan Takhta
Di awal pemerintahannya, Raden Mas Jatmika bergelar Susuhunan Anyakrakusuma dan juga dikenal sebagai Prabu Pandita Anyakrakusuma. Setelah menaklukkan Madura pada tahun 1624, beliau mengubah gelarnya menjadi Susuhunan Agung Adi Prabu Anyakrakusuma atau Sunan Agung.
Pada tahun 1641, utusan Sultan Agung kembali dari Makkah dengan membawa gelar sultan dari perwakilan syarif Makkah, Zaid ibnu Muhsin Al Hasyimi. Gelar tersebut adalah Sultan Abdullah Muhammad Maulana Matarani al-Jawi, disertai kuluk untuk mahkotanya, bendera, pataka, dan sebuah guci berisi air zamzam. Guci tersebut kini berada di makam Astana Kasultanagungan di Imogiri dengan nama Enceh Kyai Mendung.
Sultan Agung menjadi penguasa Mataram pada tahun 1613 M saat berusia 20 tahun, menggantikan Pangeran Martapura yang memerintah hanya satu hari. Secara teknis, Sultan Agung adalah sultan Mataram keempat, tetapi umumnya dianggap sebagai sultan ketiga.
Pemerintahan dan Perjuangan
Saat penobatan Sultan Agung, ibu kota Mataram masih berada di Kotagede. Pada 1614, sebuah istana baru dibangun di Karta, sekitar 5 km di barat daya Kotagede, yang mulai ditempati 4 tahun kemudian.
Pendudukan Belanda di ujung barat Jawa, sepanjang Banten, dan pemukiman Belanda di Batavia merupakan wilayah di luar kendali Sultan Agung. Dalam upayanya mempersatukan Jawa, Sultan Agung menganggap keberadaan Belanda di Batavia sebagai ancaman terhadap hegemoni Mataram.
Pada 1628, Sultan Agung dan pasukan Mataram mulai menyerbu Belanda di Batavia. Tahap awal serangan terbukti sulit karena kurangnya dukungan logistik. Sultan Agung kembali menyerang Batavia pada tahun berikutnya dengan total 14.000 orang prajurit. Meskipun serangan kedua berhasil membendung dan mengotori sungai Ciliwung yang mengakibatkan wabah penyakit kolera di Batavia dan menyebabkan kematian Gubernur Jenderal Belanda J.P. Coen, serangan tersebut akhirnya tidak berhasil mengusir Belanda dari Batavia karena pasukan Mataram juga terkena wabah penyakit malaria dan kolera.
Warisan Budaya dan Administrasi
Sultan Agung dikenal sebagai budayawan yang mendorong perkembangan tarian bedaya sebagai tarian sakral, gamelan, dan wayang. Beliau juga merupakan pendiri kalender Jawa yang masih digunakan hingga saat ini dan penulis karya sastra berjudul Serat Sastra Gendhing, yang membahas filosofi hubungan sastra dan gendhing serta ajaran-ajaran mengenai hubungan kosmis antara manusia dengan Tuhan.
Di lingkungan keraton Mataram, Sultan Agung membentuk bahasa standar yang disebut bahasa Bagongan, digunakan oleh para bangsawan dan pejabat Mataram untuk menghilangkan kesenjangan di antara para bangsawan dan keluarga raja. Pengaruh politik feodal Sultan Agung juga menjadikan diberlakukannya penggunaan tingkatan bahasa di wilayah Jawa Barat.
Warisan utama Sultan Agung terletak pada reformasi administrasi yang ia lakukan di wilayah kekuasaannya. Beliau menciptakan struktur administrasi yang inovatif dan rasional dengan membentuk "provinsi" dan menunjuk orang sebagai Adipati sebagai kepala wilayah Kadipaten, khususnya di bagian barat Jawa. Struktur administrasi ini kemudian dipertahankan oleh pemerintah Hindia Belanda dan menjadi dasar sistem pemerintahan daerah di Indonesia modern.
Pengakuan dan Penghargaan
Atas jasa-jasanya sebagai pejuang dan budayawan, Sultan Agung telah ditetapkan menjadi pahlawan nasional Indonesia berdasarkan S.K. Presiden No. 106/TK/1975 tanggal 3 November 1975. Sultan Agung hingga kini dihormati di Jawa secara kontemporer baik karena perjuangannya membela tanah air maupun warisan tradisi dan budaya yang ia sumbangkan untuk negara.