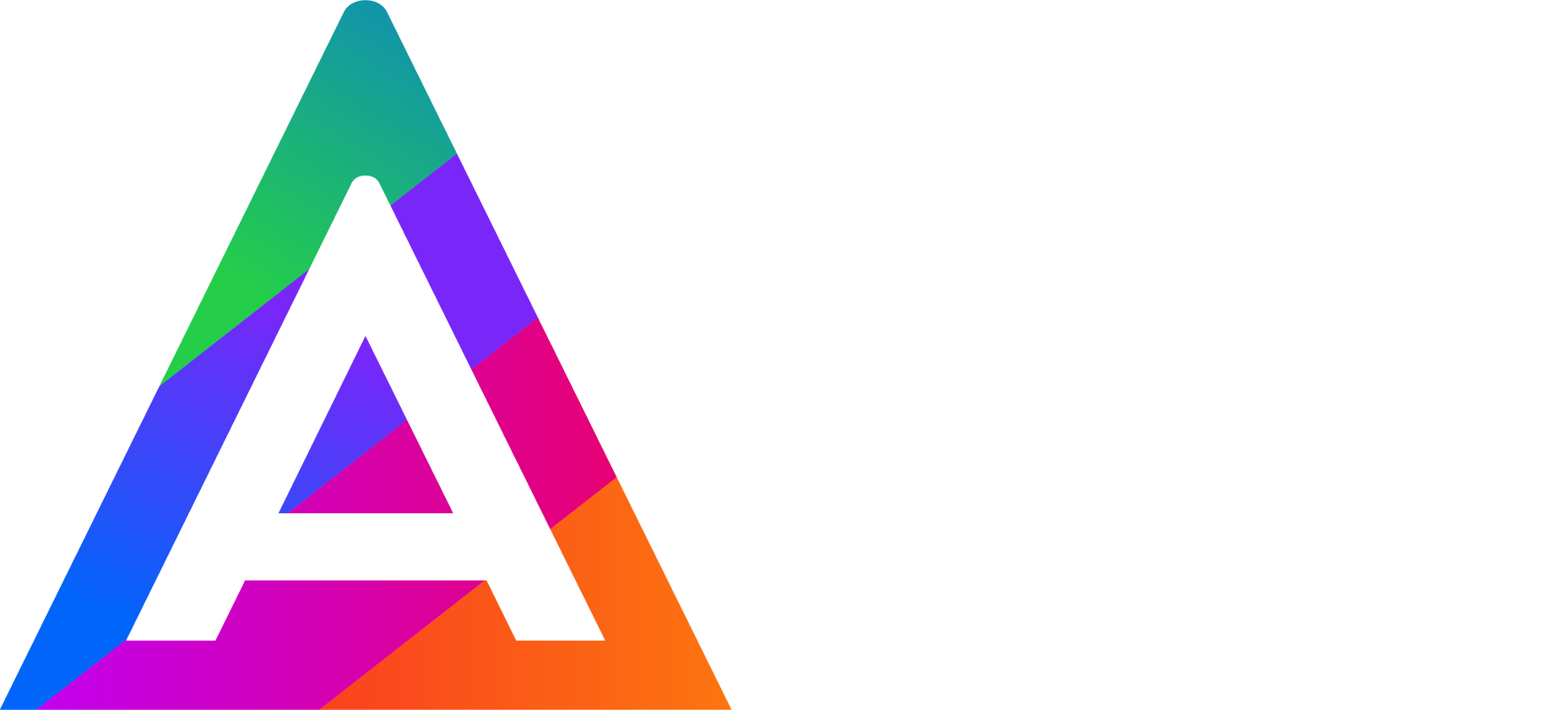Tari Bedaya Ketawang merupakan tarian sakral dan kebesaran Keraton Kasunanan Surakarta yang memiliki nilai historis dan filosofis mendalam. Tarian ini hanya dipertunjukkan pada peristiwa penting yaitu saat penobatan dan peringatan kenaikan tahta Raja Surakarta (Tingalandalem Jumenengan). Kata "bedhaya" merujuk pada penari wanita istana, sementara "ketawang" berarti langit, melambangkan ketinggian, keluhuran, dan kemuliaan.
Sejarah
Terdapat beberapa versi mengenai asal-usul Tari Bedaya Ketawang. Versi pertama menceritakan Sultan Agung Hanyakrakusuma, penguasa Kesultanan Mataram (1613-1645), yang ketika sedang melakukan semadi (meditasi) mendengar senandung dari arah langit (tawang). Terpesona oleh senandung tersebut, Sultan Agung kemudian menciptakan tarian yang diberi nama Bedaya Ketawang. Dalam proses penciptaan ini, Sultan Agung dibantu oleh empat pengikutnya: Panembahan Purbaya, Kyai Panjang Mas, Pangeran Karang Gayam II, dan Tumenggung Alap-Alap.
Versi lain mengisahkan bahwa tarian ini berasal dari pertemuan spiritual antara Panembahan Senapati (pendiri Dinasti Mataram) dengan Kanjeng Ratu Kidul atau Ratu Kencanasari (penguasa laut selatan) yang kemudian menjalin hubungan asmara. Pertemuan spiritual dan kisah cinta ini diyakini menjadi cikal bakal terciptanya Tari Bedaya Ketawang.
Setelah Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 yang membagi Kesultanan Mataram menjadi Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta, Tari Bedaya Ketawang menjadi bagian dari warisan budaya yang dimiliki Kasunanan Surakarta. Hingga saat ini, tarian tersebut masih dipertahankan sebagai bagian penting dalam upacara kerajaan.
Penari dan Makna Filosofis
Tari Bedaya Ketawang dibawakan oleh sembilan penari perempuan yang masing-masing memiliki peran dan posisi simbolis:
1. Batak: melambangkan pikiran dan jiwa
2. Endhel Ajeg: melambangkan keinginan hati atau nafsu
3. Endhel Weton: melambangkan tungkai kanan
4. Apit Ngarep: melambangkan lengan kanan
5. Apit Mburi: melambangkan lengan kiri
6. Apit Meneg: melambangkan tungkai kiri
7. Gulu: melambangkan badan
8. Dhada: melambangkan badan
9. Buncit: melambangkan organ seksual dan konstelasi bintang sebagai simbol langit (tawang)
Dalam tradisi kepercayaan Jawa, formasi sembilan penari ini diyakini melambangkan sembilan arah mata angin (Nawasanga) yang dikuasai oleh sembilan dewa. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, ketika tarian ini dipertunjukkan, Kanjeng Ratu Kidul hadir sebagai penari kesepuluh yang tak kasat mata.
Persyaratan dan Tata Cara
Sebagai tarian sakral, Tari Bedaya Ketawang mensyaratkan kriteria khusus bagi para penarinya. Syarat utama adalah penari harus seorang gadis suci dan tidak sedang haid. Jika seorang penari sedang haid, ia tetap diperbolehkan menari dengan syarat harus meminta izin kepada Kanjeng Ratu Kidul melalui ritual caos dhahar (persembahan makanan) di Panggung Sangga Buwana, Keraton Surakarta.
Para penari juga harus suci secara batiniah dengan cara berpuasa selama beberapa hari menjelang pertunjukan. Kesucian para penari sangat diperhatikan karena menurut kepercayaan, Kanjeng Ratu Kidul akan menghampiri para penari yang gerakannya masih keliru saat latihan.
Busana dan Perlengkapan
Busana yang dikenakan oleh para penari Bedaya Ketawang adalah dodot ageng atau basahan, yaitu busana yang biasanya digunakan oleh pengantin perempuan Jawa. Para penari menggunakan gelung bokor mengkurep (sanggul berukuran besar) yang ukurannya lebih besar dibandingkan dengan gaya Yogyakarta.
Aksesoris yang dikenakan para penari meliputi centhung, garudha mungkur, sisir jeram saajar, cundhuk mentul, dan tiba dhadha (rangkaian bunga melati yang dikenakan di sanggul dan memanjang hingga dada bagian kanan). Busana Tari Bedaya Ketawang didominasi warna hijau, yang menunjukkan bahwa tarian ini menggambarkan kisah asmara Kanjeng Ratu Kidul dengan raja-raja Mataram.
Iringan Musik
Iringan musik Tari Bedaya Ketawang disebut Gending Ketawang Gedhe yang bernada pelog. Perangkat gamelan yang digunakan terdiri dari lima jenis instrumen utama: kethuk, kenong, kendhang, gong, dan kemanak yang sangat mendominasi keseluruhan irama gending.
Tarian ini dibagi menjadi tiga adegan (babak). Di tengah tarian, laras (nada) gending berganti menjadi nada slendro selama dua kali, kemudian kembali lagi ke laras pelog hingga tarian berakhir. Pada bagian pertama, tarian diiringi dengan tembang Durma, selanjutnya berganti ke Retnamulya. Saat mengiringi jalannya penari kembali ke Dalem Ageng Prabasuyasa, alat gamelan yang dimainkan ditambah dengan rebab, gender, gambang, dan suling untuk menambah keselarasan suasana.
Durasi Pertunjukan
Pada masa awal, Tari Bedaya Ketawang dipertunjukkan selama dua setengah jam. Namun sejak masa pemerintahan Pakubuwana X, durasi tarian ini dikurangi menjadi satu setengah jam.
Nilai Kultural dan Historis
Tari Bedaya Ketawang bukan sekadar hiburan, melainkan tarian yang memiliki makna filosofis mendalam tentang hubungan manusia dengan alam dan kekuatan adikodrati. Tarian ini menggambarkan hubungan asmara antara Kanjeng Ratu Kidul dengan raja-raja Mataram, yang diwujudkan dalam gerak-gerik tangan, seluruh bagian tubuh, dan cara memegang sondher (selendang).
Tembang yang mengiringi tarian ini mengandung ungkapan curahan asmara Kanjeng Ratu Kidul kepada raja. Sebagai warisan budaya yang telah bertahan selama berabad-abad, Tari Bedaya Ketawang menjadi bukti keberlanjutan tradisi dan identitas budaya Jawa, khususnya Keraton Surakarta.