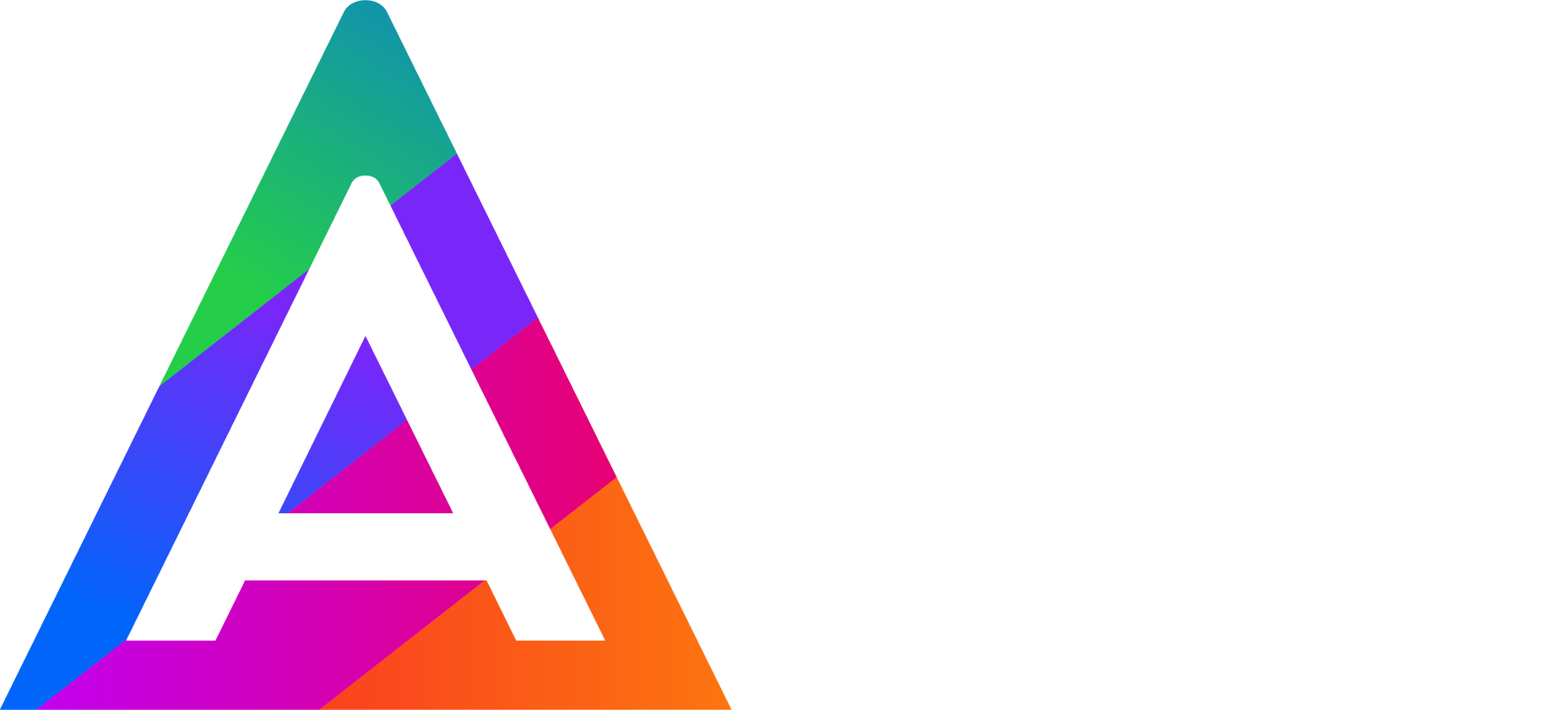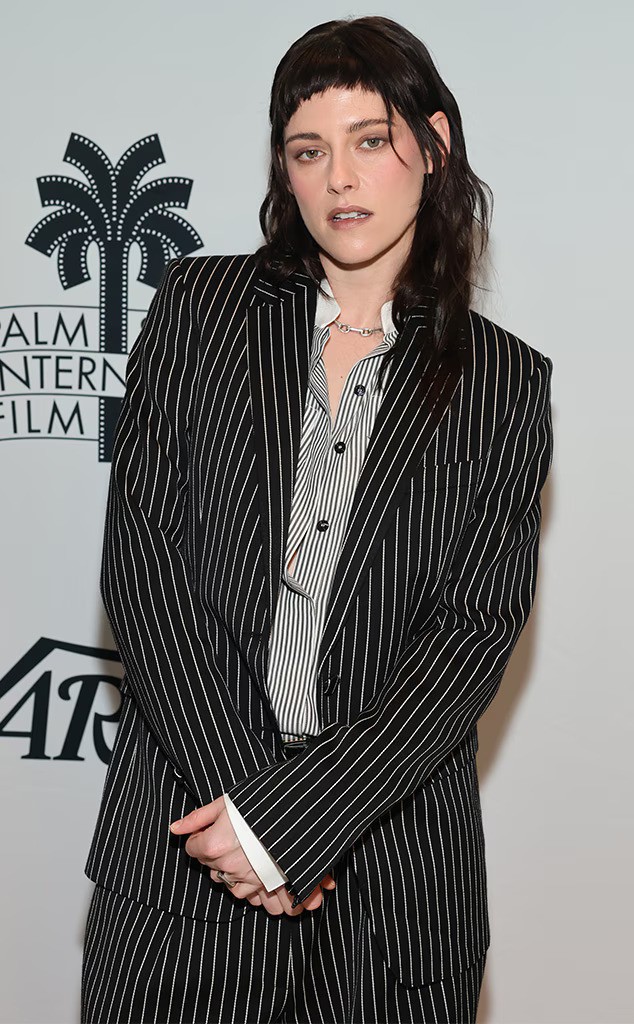Industri perfilman horor Indonesia kembali menghadirkan sebuah karya yang seharusnya menjadi puncak dari franchise Pamali, namun justru berakhir sebagai kemunduran yang mengecewakan. Pamali: Tumbal, film ketiga dalam seri adaptasi game horor populer ini, dirilis pada 7 Agustus 2025 dengan ekspektasi tinggi dari penggemar yang telah mengikuti perjalanan sinematik sejak Pamali (2022) dan Pamali: Dusun Pocong (2023). Sayangnya, harapan tersebut harus kandas di tengah eksekusi yang terkesan asal-asalan dan kehilangan identitas yang menjadi kekuatan franchise sebelumnya.
Disutradarai dengan pendekatan yang terlalu aman dan mudah ditebak, film ini mengambil latar cerita dari DLC game Pamali: The Little Devil yang mengangkat sosok tuyul sebagai antagonis utama. Namun, alih-alih memberikan inovasi segar dalam lanskap horor Indonesia, Pamali: Tumbal justru terjebak dalam formula klise yang telah berkali-kali disajikan dalam sinema horor Tanah Air. Keputusan untuk menghadirkan tuyul sebagai hantu utama sebenarnya cukup menarik, mengingat sosok setan anak kecil pencuri uang ini memang sudah lama absen dari layar lebar Indonesia. Namun, eksekusi yang setengah hati membuat potensi tersebut menjadi sia-sia belaka.
Cerita dimulai dengan penggambaran kondisi ekonomi yang memilukan di sebuah desa terpencil, dimana populasi wanita dewasa semakin menipis karena fenomena hilangnya ibu-ibu secara misterius setiap tahunnya. Ambar, yang diperankan oleh Djenar Maesa Ayu, menjadi salah satu korban dari fenomena ini setelah terpaksa mengambil uang tumbal akibat tekanan ekonomi yang mencekik. Sebagai janda yang harus menghidupi dua anaknya, Ambar akhirnya menjadi mangsa empuk bagi kekuatan supernatural yang menguasai desa tersebut.
Putri, protagonis yang diperankan Keisya Levronka, harus mencari ibunya yang menghilang dengan berbekal petunjuk samar berupa igauan tentang "corong ireng" atau cerobong hitam. Bersama dua temannya, dia menjelajahi pabrik kimia tua milik mantan Kepala Desa yang menjadi sarang dari kekuatan jahat yang telah lama mengintai warga desa. Dari sinilah, narasi film berubah menjadi petualangan horor konvensional dengan segala klise yang dapat diprediksi dari mil jauhnya.
Aspek sinematografi memang layak mendapat apresiasi dalam karya ini. Pencahayaan gelap yang mendominasi hampir seluruh durasi film berhasil menciptakan atmosfer mencekam yang sesuai dengan genre horor. Penggunaan setting pabrik tua dan hutan angker juga memberikan latar yang tepat untuk membangun ketegangan. Desain suara dan scoring musik, meskipun kadang berlebihan hingga menyakitkan telinga, mampu memberikan efek mengejutkan yang diharapkan dalam film horor. Namun, kelebihan teknis ini tidak mampu menutupi kelemahan fundamental dalam aspek naratif yang menjadi tulang punggung sebuah karya sinema.
Permasalahan utama terletak pada struktur cerita yang terlalu linear dan mudah ditebak. Sejak menit-menit awal, penonton sudah dapat memprediksi alur yang akan terjadi, termasuk plot twist yang seharusnya mengejutkan namun justru terasa dipaksakan. Dialog-dialog seperti "ini jangan dilanggar" atau peringatan serupa terasa seperti undangan bagi penonton untuk menebak bahwa larangan tersebut pasti akan dilanggar oleh karakter dalam film. Konstruksi naratif yang demikian menunjukkan kemalasan dalam penulisan skenario yang seharusnya menjadi kekuatan utama sebuah karya horor.
Pengembangan karakter juga menjadi kelemahan mencolok dalam film ini. Putri sebagai protagonis utama tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan sepanjang film. Keputusannya untuk langsung menduga bahwa ibunya berada di pabrik kimia terasa tidak masuk akal dan kurang memiliki dasar yang kuat. Alih-alih fokus mencari ibunya yang hilang, karakter ini malah terjebak dalam urusan-urusan sampingan yang tidak berkontribusi terhadap perkembangan plot utama. Karakter-karakter pendukung seperti Aji yang hanya memberikan informasi tentang igauan sang ibu, Om Dean yang kehadirannya tampak dipaksakan untuk menarik perhatian penonton, dan Tembong yang tidak jelas motivasinya dalam cerita, semuanya terasa seperti pengisi ruang kosong tanpa memberikan substansi berarti.
Aspek komedi yang diselipkan dalam film ini menghadirkan dilema tersendiri. Di satu sisi, kehadiran Cecep sebagai comic relief mampu memberikan momen-momen jenaka yang menghibur dan membuat film ini masih dapat ditonton hingga akhir. Interaksi antara Cecep dan Kiki memberikan dinamika yang segar di tengah ketegangan horor yang monoton. Namun di sisi lain, terlalu banyak elemen komedi justru mengurangi intensitas ketegangan yang seharusnya menjadi kekuatan utama film horor. Beberapa momen komedi bahkan terasa cringe dan tidak pada tempatnya, sehingga merusak mood horor yang sudah susah payah dibangun.
Kehadiran tuyul sebagai hantu utama sebenarnya membawa potensi besar untuk mengeksplorasi kekayaan mitologi Indonesia. Lore atau cerita latar belakang tuyul dijelaskan dengan cukup komprehensif sesuai dengan kepercayaan tradisional masyarakat Indonesia. Tuyul digambarkan sebagai hantu anak-anak yang tidak dapat menua dan bertugas mencuri uang untuk majikannya. Proses perawatan tuyul yang melibatkan "ibu" untuk menyusuinya dengan darah, bukan ASI, serta tradisi tumbal yang melibatkan uang yang ditemukan di jalan, semuanya dijelaskan dengan detail yang menunjukkan riset yang memadai terhadap folklore Indonesia.
Namun, visualisasi tuyul melalui teknologi CGI justru menjadi bumerang bagi film ini. Alih-alih menciptakan sosok yang mengerikan, tuyul dalam film ini tampak seperti karakter video game yang tidak berhasil menyatu dengan realisme sinematik. Desain bocah tua dengan kepala besar, gigi taring, dan lidah panjang yang menjulur terlihat lebih lucu daripada menakutkan. Keputusan untuk menggunakan animasi digital alih-alih aktor sungguhan mungkin memang sesuai dengan konsep adaptasi dari game, namun hasilnya tidak memuaskan secara visual dan mengurangi dampak psikologis yang seharusnya ditimbulkan oleh sosok hantu tersebut.
Ironisnya, penonton justru lebih merasa terintimidasi oleh kehadiran kuntilanak, terutama varian kuntilanak hitam yang muncul dalam film ini. Hal ini menunjukkan bahwa fokus pada tuyul sebagai selling point utama tidak berhasil mencapai tujuannya. Bahkan dalam beberapa scene, kemunculan tuyul justru memancing tawa alih-alih ketakutan, yang tentu saja kontradiktif dengan tujuan utama film horor.
Jumpscare yang menjadi andalan utama film horor Indonesia kontemporer memang masih cukup efektif dalam memberikan efek kejutan sesaat. Namun, ketergantungan berlebihan pada teknik ini menunjukkan kemiskinan kreativitas dalam membangun ketegangan psikologis yang berkelanjutan. Fake jumpscare yang terlalu sering digunakan malah membuat penonton menjadi kebal terhadap efek kejutan yang diharapkan. Ditambah lagi, penggunaan suara keras yang berlebihan saat jumpscare muncul terkesan seperti cara instan untuk mengejutkan penonton tanpa mempertimbangkan kenyamanan menonton secara keseluruhan.
Masalah dalam pacing atau ritme cerita juga sangat terasa sepanjang durasi film yang sekitar 90 menit ini. Bagian pembuka yang seharusnya membangun world-building dan karakterisasi terasa terburu-buru, sementara bagian tengah menjadi sangat lambat dan repetitif. Ketika memasuki klimaks, penyelesaian konflik terasa terlalu cepat dan dipaksakan, seolah-olah pembuat film ingin segera mengakhiri penderitaan penonton. Pacing yang tidak konsisten ini membuat pengalaman menonton menjadi tidak nyaman dan sulit untuk terlibat secara emosional dengan cerita yang disajikan.
Penggunaan bahasa Jawa yang setengah-setengah dalam dialog juga menjadi elemen mengganggu yang mengurangi kualitas sinematik film ini. Alih-alih memberikan keaslian budaya lokal yang kuat, penggunaan bahasa daerah yang tidak konsisten dan terkesan dipaksakan justru menyiksa pendengaran penonton. Hal ini menunjukkan kurangnya perhatian terhadap detail yang sebenarnya dapat menjadi kekuatan untuk membangun identitas lokal yang autentik.
Aspek misterius yang seharusnya menjadi daya tarik utama dalam film horor juga tidak berhasil dikelola dengan baik. Misteri hilangnya para ibu di desa tersebut tidak dikembangkan dengan layer yang kompleks dan menarik. Alih-alih memberikan clue yang menantang penonton untuk berpikir, film ini justru memberikan jawaban yang terlalu mudah dan tidak memuaskan. Plot hole atau lubang cerita juga bertebaran di berbagai bagian, menunjukkan kurangnya perhatian terhadap konsistensi naratif yang seharusnya menjadi prioritas utama.
Tema pamali atau pantangan dalam budaya Indonesia yang menjadi trademark franchise ini juga tidak tereksplorasi dengan mendalam. Konsep pamali lebih berfungsi sebagai gimmick untuk menghubungkan film ini dengan seri sebelumnya, bukan sebagai elemen naratif yang substansial. Padahal, eksplorasi mendalam terhadap berbagai pamali dalam budaya Indonesia dapat memberikan kekayaan cerita yang unik dan berbeda dari film horor internasional pada umumnya.
Performa akting dalam film ini menunjukkan ketimpangan yang cukup mencolok. Keisya Levronka sebagai pemeran utama memberikan performa yang cukup baik dan menjadi satu-satunya saving grace dari segi akting dalam film ini. Namun, performa aktor-aktor pendukung lainnya terkesan datar dan tidak meyakinkan. Dialog yang disampaikan terasa tidak natural dan kurang menghayati situasi yang sedang dihadapi karakter. Hal ini membuat penonton sulit untuk berempati atau peduli terhadap nasib karakter-karakter dalam film.
Keputusan karakter yang tidak logis juga menjadi ciri khas yang sayangnya masih bertahan dalam film horor Indonesia. Karakter-karakter dalam Pamali: Tumbal membuat keputusan-keputusan yang sangat bodoh dan tidak masuk akal, bahkan dalam standar film horor sekalipun. Alih-alih membuat penonton khawatir terhadap nasib mereka, keputusan-keputusan bodoh ini justru membuat karakter terlihat annoying dan tidak layak untuk diselamatkan.
Ending atau penutup cerita juga menjadi aspek yang paling mengecewakan dari keseluruhan film ini. Resolusi konflik terasa terburu-buru dan tidak memberikan kepuasan emosional yang diharapkan penonton. Klimaks yang seharusnya menjadi puncak ketegangan malah terasa anti-klimaks karena tidak dipersiapkan dengan build-up yang memadai. Kesan bahwa film ini hanya berfungsi sebagai jembatan untuk mengantarkan ke misteri selanjutnya di Dusun Pocong sangat terasa, seolah-olah film ini tidak memiliki identitas yang berdiri sendiri.
Dari perspektif industri, Pamali: Tumbal menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan dalam perkembangan perfilman horor Indonesia. Ketergantungan pada formula yang sudah terbukti marketable tanpa inovasi berarti akan membuat genre horor lokal stagnan dan kehilangan daya saingnya. Film ini seolah-olah dibuat dengan mentalitas "yang penting jadi" tanpa mempertimbangkan kualitas artistik dan naratif yang seharusnya menjadi prioritas utama.
Sebagai bagian dari universe Pamali yang memiliki potensi besar untuk mengeksplorasi kekayaan budaya dan mitologi Indonesia, film ini justru menjadi langkah mundur yang signifikan. Padahal, dengan source material berupa game yang sudah memiliki fanbase loyal, seharusnya film ini dapat menjadi adaptasi yang membanggakan dan mengangkat martabat sinema horor Indonesia ke level yang lebih tinggi.
Dalam konteks perbandingan dengan film-film horor Indonesia lainnya, Pamali: Tumbal tidak berhasil memberikan sesuatu yang baru atau berbeda. Semua elemen yang disajikan sudah pernah dilihat dalam puluhan film horor Indonesia sebelumnya, dengan kualitas eksekusi yang bahkan lebih rendah. Hal ini menunjukkan kurangnya research dan development yang memadai dalam proses pra-produksi film.
Namun demikian, tidak semua aspek dalam film ini buruk total. Upaya untuk mengangkat kembali sosok tuyul yang memang sudah lama tidak muncul dalam perfilman Indonesia patut diapresiasi sebagai langkah berani untuk mengeksplorasi folklore yang kurang populer. Riset terhadap lore tuyul juga menunjukkan keseriusan dalam memahami akar budaya yang menjadi source material. Beberapa momen komedi yang berhasil juga memberikan variasi dalam ritme cerita yang monoton.
Secara keseluruhan, Pamali: Tumbal adalah sebuah karya yang gagal memenuhi potensinya sendiri. Film yang seharusnya menjadi puncak dari franchise Pamali ini justru berakhir sebagai kemunduran yang mengecewakan penggemar dan kritikus. Dengan segala kekurangan yang ada, mulai dari naratif yang lemah, visualisasi hantu yang tidak memuaskan, karakter yang tidak berkembang, hingga pacing yang tidak konsisten, film ini sulit untuk direkomendasikan bahkan kepada penggemar setia genre horor Indonesia.
Kegagalan Pamali: Tumbal seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi industri perfilman Indonesia untuk tidak mengandalkan popularitas brand tanpa memperhatikan kualitas konten yang disajikan. Adaptasi dari video game memang memiliki tantangan tersendiri, namun bukan berarti tidak dapat diwujudkan dengan kualitas yang memuaskan jika dikerjakan dengan persiapan dan dedikasi yang memadai.
Untuk ke depannya, franchise Pamali masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kualitasnya jika pembuat film mau belajar dari kesalahan yang terjadi dalam film ketiga ini. Eksplorasi yang lebih mendalam terhadap mitologi Indonesia, pengembangan karakter yang lebih matang, dan inovasi dalam teknik storytelling horor dapat menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan penonton terhadap brand Pamali.
Film ini lebih cocok ditonton sebagai hiburan ringan tanpa ekspektasi tinggi, atau sebagai studi kasus tentang bagaimana tidak seharusnya sebuah film horor diproduksi. Bagi penonton yang mengharapkan pengalaman horor yang berkualitas, lebih baik mencari alternatif lain yang lebih layak untuk menghabiskan waktu dan uang.
Pamali: Tumbal akhirnya menjadi bukti bahwa popularitas brand saja tidak cukup untuk menjamin kualitas sebuah karya sinema. Tanpa fondasi naratif yang kuat dan eksekusi yang matang, bahkan franchise yang sudah memiliki fanbase loyal dapat kehilangan kredibilitasnya dalam sekejap mata. Semoga saja, kegagalan ini tidak menjadi akhir dari eksplorasi sinematik terhadap kekayaan folklore Indonesia, melainkan awal dari pembelajaran untuk menciptakan karya-karya horor lokal yang lebih berkualitas di masa mendatang.