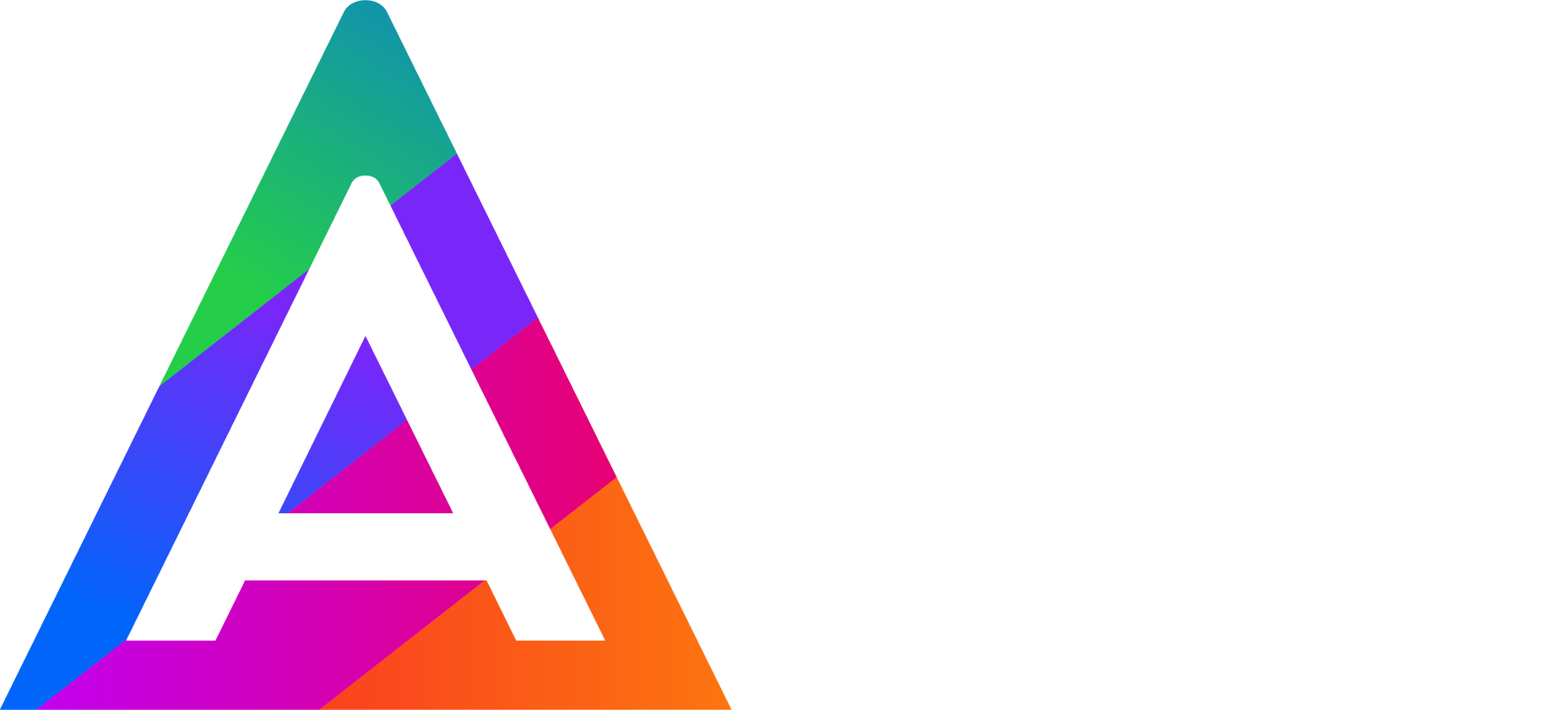Film adaptasi Korea yang ambisius namun terjebak dalam klise dramatisasi
Film Panggil Aku Ayah hadir sebagai upaya ambisius remake dari film Korea Selatan Pawn (2020) yang diproduksi oleh Visinema Studios bekerja sama dengan CJ-ENM. Sutradara Benni Setiawan mencoba mengangkat isu fenomena fatherless dalam masyarakat Indonesia kontemporer dengan latar Sukabumi, Jawa Barat. Namun, sebagai kritikus yang telah menyaksikan berbagai karya tearjerker domestik dan internasional, harus diakui bahwa film ini mengalami dilema klasik: terjebak antara keinginan menyentuh hati penonton dengan kebutuhan mempertahankan kredibilitas naratif.
Premis yang Menjanjikan dengan Eksekusi Setengah Hati
Cerita bermula dari Dedi (Ringgo Agus Rahman) dan Tatang (Boris Bokir), dua debt collector yang memiliki karakter anomali menarik - preman berjiwa baik hati. Keduanya terpaksa menjadi "pengasuh dadakan" ketika gadis kecil bernama Intan alias "Pacil" (Myesha Lin) dijadikan jaminan akibat sang ibu Rossa (Sita Nursanti) tak mampu melunasi utang. Apa yang seharusnya menjadi pengasuhan sementara selama seminggu berubah menjadi komitmen bertahun-tahun hingga Intan (Tissa Biani dalam versi dewasa) beranjak dewasa.
Konsep dasar ini sesungguhnya kuat dan relevan. Indonesia menghadapi realitas sosial dimana banyak anak tumbuh tanpa figur ayah, baik karena perceraian, kematian, atau faktor ekonomi yang memaksa ayah merantau. Film ini mencoba mengeksplorasi bagaimana sosok pengganti dapat mengisi kekosongan emosional tersebut. Sayangnya, eksekusi naratif tidak selalu konsisten dengan premis yang menjanjikan ini.
Kekuatan Naskah Rifki Ardisha dalam Membangun Hubungan Karakter
Salah satu aspek terpuji dari film ini terletak pada naskah buatan Rifki Ardisha yang masih memperhatikan logika sebab-akibat dalam membangun relasi antar karakter. Transformasi Dedi dari seorang penagih utang menjadi figur ayah tidak terjadi secara ajaib atau dipaksakan. Prosesnya dibangun melalui serangkaian momen kecil dimana Dedi merasakan bahwa Pacil adalah satu-satunya orang yang melihatnya lebih dari sekadar profesinya yang keras.
Begitu pula dengan Pacil, peralihan dari penolakan awal menuju penerimaan terhadap Dedi dan Tatang digambarkan melalui tahapan yang dapat dipahami. Ini bukan sekadar Stockholm syndrome, melainkan proses psikologis natural dimana seorang anak mencari figur protektif di tengah ketidakpastian hidupnya. Naskah berhasil menunjukkan bahwa ikatan keluarga tidak selalu terbentuk dari hubungan darah, melainkan dari keputusan untuk saling merawat dan bertanggung jawab.
Elemen budaya lokal juga terintegrasi dengan baik. Pemilihan nama "Dedi" dan julukan "Pacil" memiliki landasan kultural yang kuat dan "sangat Indonesia". Lebih menarik lagi, penggunaan lagu "Tegar" milik Rossa yang dialihfungsikan dari lagu cinta menjadi representasi maternal love menunjukkan kecerdikan dalam adaptasi budaya populer untuk kepentingan naratif.
Performa Akting yang Menyelamatkan dari Berbagai Kekurangan
Ringgo Agus Rahman sekali lagi membuktikan kemampuannya sebagai aktor yang dapat menyelamatkan film dari berbagai kelemahan teknis dan naratif. Perannya sebagai Dedi tidak jatuh ke dalam stereotip preman jahat atau sebaliknya, preman yang tiba-tiba menjadi malaikat. Ringgo berhasil menampilkan kompleksitas karakter yang tetap mempertahankan sisi keras profesinya sambil mengembangkan sisi protektif dan kasih sayang.
Momen puncak aktingnya terletak pada adegan dimana Dedi akhirnya mendengar Pacil memanggilnya "ayah". Ekspresi campur aduk yang ditampilkan Ringgo - antara haru, bangga, terharu, dan sekaligus menyadari tanggung jawab besar yang dipercayakan kepadanya - terasa autentik tanpa berlebihan. Inilah yang membedakan akting berkualitas dengan sekadar dramatisasi.
Boris Bokir sebagai Tatang juga memberikan performa solid sebagai karakter pendukung yang tidak hanya berfungsi sebagai comic relief. Kehadiran Tatang memberikan dinamika buddy system yang memperkaya naratif utama tanpa mengganggu fokus cerita pada relasi Dedi-Pacil.
Myesha Lin, meskipun baru berusia tujuh tahun, menunjukkan kemampuan akting yang mengejutkan. Tidak mudah bagi anak sekecil itu untuk memahami dan mengekspresikan konflik emosional karakter yang harus berpindah dari satu situasi traumatis ke penerimaan terhadap keluarga baru. Myesha berhasil melakukannya dengan natural tanpa terkesan dipaksa atau berlebihan.
Sita Nursanti dalam perannya yang relatif terbatas berhasil menampilkan dilema seorang ibu yang terpaksa meninggalkan anak karena tekanan ekonomi. Momennya saat menyanyikan lagu "Tegar" menjadi salah satu puncak emosional film yang terasa tulus.
Keunggulan Sinematografi dan Desain Produksi
Tim artistik film ini patut diapresiasi untuk pilihan visualnya yang tidak jatuh ke dalam jebakan kemiskinan yang dieksploitasi atau sebaliknya, kemewahan yang tidak masuk akal. Kostum yang dikenakan karakter serta properti rumah menciptakan perpaduan warna yang natural tanpa terlihat artifisial. Ada keseimbangan dalam menampilkan kesederhanaan tanpa membuat penonton merasa dikasihani atau sebaliknya, merasa tidak relate.
Bahkan dalam beberapa momen, busana dan properti menciptakan sinkronisasi warna secara subtil yang menunjukkan kejelian tim artistik. Latar Sukabumi juga dipilih dengan tepat, memberikan nuansa lokal yang kuat tanpa terkesan memaksa eksotisme daerah.
Penggunaan bahasa Sunda terasa natural, terutama dalam dialog Ringgo dan Boris yang memang berlatar belakang Sunda. Tidak seperti beberapa film Indonesia yang menggunakan bahasa daerah secara paksa atau bahkan keliru, di sini terasa mengalir sebagai bagian organic dari karakter dan setting.
Problem Serius di Babak Ketiga: Kehilangan Momentum Naratif
Namun, semua keunggulan yang telah dibangun dengan baik di dua babak pertama praktis hancur di babak ketiga. Inilah kelemahan fatal yang membuat film ini gagal menjadi karya yang benar-benar berkesan. Babak ketiga terasa kacau dengan kerancuan linimasa yang membingungkan. Penonton yang seharusnya dibawa ke klimaks emosional justru dibuat pusing dengan alur yang tiba-tiba berubah dan tidak konsisten.
Lebih parah lagi, konklusi disajikan dengan sangat terburu-buru seolah-olah sutradara enggan memberikan ruang bagi penonton untuk benar-benar meresapi luapan perasaan yang mestinya hadir. Padahal, film tearjerker yang baik justru harus memberikan waktu yang cukup untuk emotional catharsis. Di sini, penonton seperti dipaksa untuk langsung "move on" tanpa sempat benar-benar merasakan dampak emosional dari perjalanan panjang karakter.
Keputusan untuk memasukkan elemen amnesia atau hilang ingatan di babak ketiga terasa seperti jalan pintas naratif yang murahan. Ini adalah klise yang sudah terlalu sering digunakan dalam drama Indonesia dan Korea, dan di film ini terasa tidak organic dengan pengembangan karakter sebelumnya. Seolah-olah penulis kehabisan ide untuk menciptakan konflik yang bermakna dan memilih elemen yang paling mudah dan prediktable.
Durasi yang Dipaksakan dan Masalah Teknis
Salah satu masalah mendasar adalah kesan bahwa film ini dipaksakan mencapai durasi dua jam. Banyak adegan di babak ketiga yang terasa bertele-tele dan tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan karakter atau plot. Ini adalah kesalahan umum dalam industri film Indonesia yang mengira bahwa durasi panjang secara otomatis menunjukkan kualitas atau kedalaman cerita.
Sebaliknya, film ini justru akan lebih kuat jika dipangkas menjadi sekitar 100 menit dengan fokus pada dua babak pertama yang solid. Kelebihan durasi malah merusak pacing dan membuat penonton kehilangan momentum emosional yang telah dibangun dengan baik.
Masalah teknis lain yang cukup mengganggu adalah beberapa adegan dubbing yang tidak mulus. Dalam beberapa momen, terlihat jelas bahwa dialog tidak sinkron dengan gerakan bibir atau ekspresi wajah aktor. Ini adalah masalah fundamental dalam produksi film yang seharusnya tidak terjadi di level studio sebesar Visinema.
Perbandingan dengan Film Asli Pawn
Sebagai adaptasi dari Pawn (2020), film ini menghadapi tantangan berat untuk melampaui atau minimal menyamai kualitas film asli. Pawn dikenal karena pendekatannya yang lebih berani dalam memvisualisasikan luka emosional dan lebih matang dalam membangun titik balik kehidupan karakter.
Film Korea tersebut juga lebih tulus dalam menyampaikan pesan tanpa terjebak dalam sentimentalisme yang berlebihan. Sementara Panggil Aku Ayah, meskipun berhasil mengadaptasi esensi cerita ke konteks Indonesia, masih terasa ragu-ragu dalam mengeksplorasi aspek gelap dari premisnya.
Namun harus diakui bahwa film ini berhasil dalam hal lokalisasi. Konteks sosial ekonomi Indonesia, khususnya fenomena breadwinner perempuan akibat ketiadaan figur ayah, terasa relevan dan autentik. Ini adalah kekuatan utama adaptasi ini dibanding sekadar meniru mentah-mentah formula aslinya.
Tema Fatherless dan Relevansinya dengan Realitas Sosial
Isu fatherless yang diangkat film ini memang sangat relevan dengan kondisi sosial Indonesia kontemporer. Banyak keluarga mengalami situasi dimana anak tumbuh tanpa figur ayah, baik karena faktor ekonomi, perceraian, atau kematian. Film ini mencoba menunjukkan bahwa peran ayah tidak harus selalu diisi oleh ayah kandung, melainkan dapat diambil alih oleh siapa saja yang bersedia bertanggung jawab dan memberikan kasih sayang.
Namun, eksplorasi tema ini tidak cukup mendalam. Film lebih fokus pada aspek emosional daripada menganalisis akar permasalahan sosial yang menyebabkan fenomena fatherless. Padahal, ini adalah kesempatan emas untuk memberikan kritik sosial yang bermakna sambil tetap menghibur penonton.
Begitu juga dengan isu ekonomi. Meskipun kemiskinan menjadi trigger utama konflik, film ini enggan mengeksplorasi lebih dalam bagaimana sistem ekonomi yang tidak adil menciptakan situasi dimana anak bisa dijadikan jaminan utang. Ini adalah missed opportunity untuk memberikan pesan sosial yang lebih kuat.
Genre Mixing yang Tidak Selalu Berhasil
Panggil Aku Ayah mencoba menggabungkan elemen komedi, drama keluarga, dan tearjerker. Dua babak pertama relatif berhasil dalam mengelola transisi antar genre ini. Komedi yang dihadirkan Boris Bokir dan Ringgo terasa natural dan tidak memaksa. Bahkan beberapa gag berhasil menciptakan tawa yang tulus tanpa merusak momentum dramatis.
Namun, di babak ketiga, genre mixing ini menjadi tidak terkendali. Film tidak tahu harus menjadi apa - apakah drama keluarga yang serius atau tearjerker yang sentimental. Akibatnya, transisi antar mood terasa tidak smooth dan membingungkan penonton.
Soundtrack dan Penggunaan Musik
Penggunaan musik dalam film ini umumnya tepat, terutama adaptasi lagu "Tegar" yang berhasil dialihfungsikan dari lagu cinta menjadi representasi kasih sayang keluarga. Ini menunjukkan kreativitas dalam memanfaatkan lagu populer untuk kepentingan naratif tanpa terkesan asal comot.
Namun, di beberapa momen, musik latar terasa terlalu manipulatif, seolah-olah memaksa penonton untuk merasakan emosi tertentu tanpa memberikan konteks yang cukup. Musik yang baik dalam film harusnya memperkuat emosi yang sudah terbangun, bukan mencoba menciptakan emosi dari nol.
Pesan Moral yang Relevan namun Tidak Mendalam
Film ini berhasil menyampaikan pesan bahwa keluarga tidak selalu terbentuk dari hubungan darah, melainkan dari komitmen untuk saling menyayangi dan melindungi. Ini adalah pesan yang universal dan relevan dengan berbagai konteks budaya.
Namun, penyampaian pesan ini tidak cukup mendalam untuk benar-benar mengubah perspektif penonton. Film lebih puas dengan menyentuh permukaan emosional daripada mengajak penonton untuk benar-benar merefleksikan nilai-nilai keluarga dan tanggung jawab sosial.
Pesan tentang pentingnya figur ayah juga tersampaikan, tetapi tidak disertai dengan analisis yang memadai tentang bagaimana mencegah atau mengatasi fenomena fatherless di masyarakat. Film ini lebih fokus pada solusi individual (Dedi mengambil peran ayah) daripada solusi sistemik.
Potensi yang Tidak Terealisasi Maksimal
Panggil Aku Ayah adalah film yang memiliki potensi besar untuk menjadi karya berkesan, tetapi gagal merealisasikan potensi tersebut secara maksimal. Dua babak pertama menunjukkan kemampuan sutradara dan penulis dalam membangun cerita yang engaging dan emosional. Akting para pemain juga solid dan meyakinkan.
Sayangnya, babak ketiga yang kacau dan keputusan-keputusan naratif yang questionable merusak keseluruhan pengalaman menonton. Film ini seperti pelari maraton yang berlari dengan baik selama 80% perjalanan tetapi terjatuh di 20% terakhir.
Dampak terhadap Industri Film Indonesia
Film ini menjadi bagian dari tren adaptasi film Korea yang semakin marak di Indonesia. Meskipun adaptasi bukan hal yang salah, perlu ada kehati-hatian agar jangan sampai industri film Indonesia menjadi terlalu bergantung pada konten luar dan kehilangan identitas originalitasnya.
Panggil Aku Ayah setidaknya berhasil dalam hal lokalisasi dan tidak terkesan seperti meniru mentah-mentah. Konteks budaya Sunda dan realitas sosial Indonesia berhasil diintegrasikan dengan baik. Ini adalah contoh positif bagaimana adaptasi seharusnya dilakukan.
Namun, kelemahan dalam eksekusi tetap menjadi catatan penting bahwa adaptasi yang baik membutuhkan lebih dari sekadar mengganti setting dan bahasa. Dibutuhkan pemahaman mendalam terhadap apa yang membuat cerita asli berkesan dan bagaimana menerjemahkannya ke konteks baru tanpa kehilangan esensinya.
Kesimpulan: Antara Harapan dan Kenyataan
Panggil Aku Ayah adalah film yang mengecewakan bukan karena buruk secara keseluruhan, melainkan karena gagal memenuhi potensi yang sudah terbangun dengan baik. Ini adalah kasus klasik film yang hampir berhasil menjadi sangat baik tetapi terjebak dalam kesalahan-kesalahan teknis dan naratif yang seharusnya bisa dihindari.
Untuk penonton umum yang mencari hiburan emosional tanpa terlalu memperhatikan konsistensi naratif, film ini mungkin masih bisa dinikmati. Akting Ringgo Agus Rahman saja sudah cukup untuk membuat film ini worth watching. Namun, untuk penonton yang mengharapkan karya sinema yang lebih matang dan konsisten, film ini akan terasa mengecewakan.
Sebagai kritikus, sulit memberikan rekomendasi penuh untuk film ini meskipun ada banyak elemen positif yang bisa diapresiasi. Film ini lebih cocok ditonton dengan ekspektasi sebagai hiburan ringan daripada sebagai karya seni yang akan meninggalkan kesan mendalam.
Dua babak pertama yang solid dan akting Ringgo Agus Rahman menyelamatkan film ini dari rating yang lebih rendah, tetapi babak ketiga yang kacau mencegah film ini mencapai rating yang lebih tinggi.
Film ini adalah pengingat bahwa dalam industri film, konsistensi sama pentingnya dengan momen-momen brilian. Tidak cukup memiliki ide bagus dan eksekusi yang baik di sebagian besar film jika tidak mampu mempertahankan kualitas hingga akhir. Panggil Aku Ayah adalah pelajaran berharga tentang pentingnya script development dan editing yang lebih ketat dalam proses produksi film Indonesia.